Identitas Nasional Indonesia: Pilar Persatuan di Tengah Keberagaman
PENDIDIKAN
Fransiskus Sehadun
9/3/20256 min read
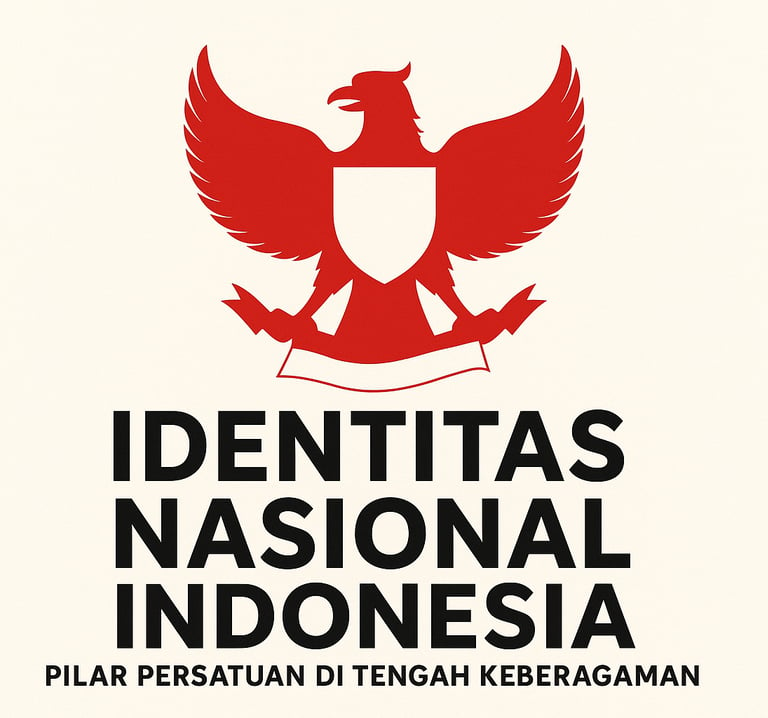

Identitas nasional adalah jati diri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, bukan sekedar simbol formal, melainkan refleksi dari nilai budaya, sejarah, dan cita-cita bersama. Secara etimologis, identitas berarti ciri atau tanda, sedangkan nasional menunjuk pada kebangsaan. Pada individu, identitas dapat diwujudkan melalui KTP atau SIM, sementara dalam lingkup bangsa, ia tampak pada Pancasila, UUD 1945, bahasa Indonesia, bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semua ini bukan hanya lambang, tetapi kristalisasi kepribadian bangsa yang diwariskan dari sejarah panjang. Winarno (2005) menegaskan bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai budaya yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Notonogoro menyebut Pancasila sebagai kristalisasi kepribadian bangsa yang menjadi dasar moral sementara itu, Magnis-Suseno menekankan bahwa identitas adalah konstruksi historis yang selalu diperbarui, bukan sesuatu yang beku.
Identitas nasional Indonesia bersifat artifisial dan sekunder. Artifisial karena lahir dari kesepakatan politik setelah berdirinya negara, sekunder karena masyarakat Indonesia sebelumnya telah memiliki identitas etnis yang beragam. Winarno (2016) menegaskan bahwa identitas nasional terbentuk melalui proses sejarah panjang yang menuntut pengorbanan kolektif, mulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi 1945. Identitas ini menjadi jembatan antara keragaman etnis dengan cita-cita bersama sebagai bangsa. Beberapa identitas yang menjadi kesepakatan bersama yakni bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu menjadi perekat komunikasi sekaligus lambang persatuan, kemudian bendera Merah Putih yang melambangkan keberanian dan kesucian telah menjadi tanda perjuangan sejak era kerajaan Nusantara. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan sejak Sumpah Pemuda mengikat semangat kebangsaan, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan komitmen persatuan dalam keragaman, kemudian Pancasila sebagai dasar filsafat negara merangkum nilai fundamental yang berakar dari jati diri bangsa. Kemudian UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi mengatur arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya NKRI sebagai bentuk negara menegaskan kedaulatan rakyat dalam bingkai kesatuan. Selanjutnya Wawasan Nusantara memperkuat kesadaran geopolitik bangsa terhadap keutuhan wilayah. Kemudian budaya daerah yang diangkat menjadi budaya nasional memperlihatkan kekayaan identitas yang tetap satu dalam perbedaan. Kemudian regulasi formal seperti UU No. 24 Tahun 2009 mengukuhkan bahasa, bendera, lambang, dan lagu kebangsaan sebagai simbol resmi negara.
Terbentuknya identitas Nasional tersebut tentunya melalui proses yang sangat Panjang yang melibatkan dimensi historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, lahirnya identitas nasional bermula dari momentum Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi bukan hanya pernyataan kemerdekaan, tetapi juga revolusi integratif yang menyatukan beragam suku, bahasa, dan budaya menjadi satu bangsa: Indonesia. Dari titik itu, kesepakatan untuk menerima Pancasila, bahasa Indonesia, dan simbol-simbol kebangsaan menjadi bukti keberhasilan bangsa ini mengatasi potensi perpecahan kemudian Secara sosiologis, identitas nasional terbentuk melalui interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya. Proses ini berlangsung sejak era pergerakan nasional, ketika rakyat Indonesia menegaskan diri sebagai “self” yang berbeda dari penjajah. Pasca kemerdekaan, interaksi antaretnis dan budaya dipererat melalui pendidikan, upacara kenegaraan, hingga kebiasaan sehari-hari. Identitas bangsa pun senantiasa bisa direkonstruksi sesuai perkembangan zaman, termasuk dalam arus globalisasi. Sementara itu, secara politis, identitas nasional dilembagakan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk identitas itu tampak jelas: bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Sang Merah Putih sebagai bendera, Garuda Pancasila sebagai lambang, hingga Pancasila sebagai dasar negara. Semua ini menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia tidak hanya lahir dari kesepakatan kultural, tetapi juga dijaga melalui legitimasi politik negara. Dengan demikian, terbentuknya identitas nasional Indonesia adalah hasil dialektika antara sejarah perjuangan, dinamika sosial-budaya, dan pengaturan politik kenegaraan. Identitas ini menjadi perekat yang memungkinkan bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri meski menghadapi tantangan perbedaan dan arus global yang terus berubah.
Tentunya di dalam Identitas Nasional tersebut memiliki unsur – Unsur Pokok seperti etnisitas dan ini merupakan unsur mendasar dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman etnis di Indonesia pada mulanya berpotensi menjadi sekat yang memisahkan, namun dalam semangat persatuan, etnisitas justru menjadi modal sosial yang memperkaya bangsa dengan dilandasi Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat etnisitas agar tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan pilar yang menopang identitas nasional. Kemudian Agama juga memiliki peran sentral dalam membentuk identitas bangsa. Indonesia dikenal sebagai bangsa religius dengan enam agama resmi yang diakui negara. Notonagoro menekankan bahwa agama berfungsi sebagai sumber moralitas publik, memberikan arah etik bagi kehidupan bersama. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Thomas Aquinas yang menekankan hukum moral alamiah sebagai dasar kehidupan sosial.Selanjutnya Kebudayaan menjadi unsur lain yang memperkaya identitas nasional. kebudayaan Indonesia bukanlah artefak mati, melainkan warisan yang terus diperbarui. Sastrapratedja menyebut jati diri bangsa sebagai konstruksi yang selalu bisa dikonstruksi ulang sesuai perjalanan sejarah. Hal ini menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar ornamen, melainkan fondasi peradaban. Di tengah arus globalisasi, kebudayaan nasional berfungsi sebagai filter agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Kemudian Bahasa Indonesia akhirnya menjadi simbol pemersatu yang paling nyata dimana dengan bahasa Indonesia dapat melampaui sekat etnis dan regional. Kaelan menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah instrumen integrasi nasional sekaligus sarana komunikasi politik bangsa. Dengan bahasa yang sama, warga negara yang berasal dari latar belakang berbeda dapat berinteraksi, berdebat, dan bermusyawarah dalam semangat kebangsaan. Bahasa, dalam hal ini, bukan hanya alat komunikasi, melainkan lambang persatuan dan identitas nasional. Pada akhirnya, identitas nasional Indonesia adalah konsensus luhur yang menegaskan siapa kita sebagai bangsa. Ia lahir dari keberagaman, disatukan oleh nilai, dan diperkuat oleh simbol-simbol negara. Aristoteles mengingatkan bahwa sebuah polis hanya dapat bertahan bila warganya memiliki kesadaran akan kesatuan tujuan. Demikian pula Indonesia: hanya dengan kesadaran kolektif, bangsa ini dapat mempertahankan eksistensinya di tengah arus globalisasi. Identitas nasional bukan sekadar milik masa lalu, melainkan warisan yang harus terus dijaga agar Indonesia tetap tegak dan bermartabat.
Disi lain bahwa terbentuknya identitas Nasional karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor primordial seperti ikatan darah, bahasa, dan adat istiadat memang mengikat masyarakat dalam kelompok kecil. Namun dalam kerangka kebangsaan, ikatan ini dilebur untuk membangun identitas nasional yang lebih luas. Begitu pula dengan faktor sakral berupa agama dan ideologi Pancasila. Keduanya memberikan pedoman moral yang menuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Tokoh pemimpin seperti Soekarno, M. Hatta M. Yamin dan masih banyak tokoh lain juga memainkan peran penting. mereka menjadi simbol persatuan sekaligus penyambung aspirasi rakyat. Pengalaman sejarah, terutama perjuangan melawan penjajahan, menjadi perekat yang menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Selain itu, pembangunan ekonomi dan keberadaan lembaga negara juga tidak bisa diabaikan. Singkatnya, identitas nasional Indonesia lahir dari perpaduan antara prinsip filosofis, nilai sakral, pengalaman sejarah, peran tokoh, hingga aspek ekonomi dan kelembagaan. Identitas ini terus berkembang, tetapi pada dasarnya berpijak pada satu cita-cita: menjaga persatuan di tengah perbedaan. Inilah kekuatan terbesar bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman.
Tentunya Identitas Nasional itu sangat penting dimana salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah keragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama, identitas nasional menjadi fondasi yang menyatukan berbagai kelompok dalam satu kesadaran kolektif sebagai bangsa Indonesia. Notonogoro menegaskan bahwa identitas nasional adalah kristalisasi kepribadian bangsa yang memberi arah moral dan hukum, sehingga persatuan bangsa terjaga. Tanpa identitas ini, perbedaan yang ada berpotensi menjadi sumber konflik dan disintegrasi. Selain itu, identitas nasional menjadi pedoman nilai dan perilaku bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara bukan sekadar simbol, tetapi memberikan arah moral dan etika yang jelas bagi warga negara. Kaelan (2007) menekankan bahwa karakter publik suatu negara adalah kualitas sosial yang membedakannya dari bangsa lain, dan hal ini diperoleh melalui internalisasi nilai-nilai identitas nasional. Identitas nasional juga berperan sebagai simbol kebanggaan dan rasa cinta tanah air. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih, dan lambang Garuda Pancasila adalah manifestasi nyata yang membangkitkan patriotisme. Magnis Suseno menambahkan bahwa identitas nasional memiliki dimensi moral yang memberi makna dan arah bagi kehidupan bangsa. Selain simbolik, identitas nasional menjadi landasan politik, hukum, dan kebijakan, agar pembangunan bangsa berpijak pada kepentingan dan jati diri bangsa. Dengan demikian identitas nasional mendukung pembangunan karakter warga negara, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat rasa memiliki. Sebagaimana ditegaskan Notonogoro, Pancasila adalah “bintang penuntun” bangsa. Identitas nasional bukan sekadar simbol, tetapi kompas moral dan praktis yang menyiapkan bangsa Indonesia menghadapi tantangan global sambil menjaga jati dirinya.
Selain memiliki tujuan Identitas juga berfungsi sebagai pembeda dengan bangsa lain sekaligus memberi ciri khas yang melekat pada bangsa ini. Identitas nasional diwujudkan melalui simbol-simbol negara selain itu Identitas ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan perwujudan nilai, sejarah, dan aspirasi bangsa. Aristoteles menekankan pentingnya kesamaan nilai dan tujuan dalam menjaga kohesi komunitas; tanpa kesamaan tersebut, masyarakat akan mudah terpecah. Kaelan (2007) menambahkan bahwa karakter publik suatu negara adalah kualitas sosial yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, yang menjadi pedoman perilaku kolektif. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai perekat yang mempersatukan seluruh warga negara. Indonesia, yang terdiri dari ratusan suku, agama, dan budaya, memerlukan titik temu untuk membangun kesadaran kolektif.
Namun demikian Identitas nasional Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi pedoman hidup sehari-hari, sering terkikis oleh kepentingan individu atau kelompok. kemudian tantangan berikutnya adalah belum sepenuhnya terinternalisasinya Pancasila dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, rasa nasionalisme dan patriotisme mulai memudar, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar arus globalisasi dan modernisasi. Hilangnya patriotisme berpotensi mengurangi partisipasi warga dalam kehidupan bernegara dan memperlemah solidaritas nasional.
Oleh karena itu dalam memperkuat identitas nasional diperlukan pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan tujuan membentuk generasi yang berintegritas dan berlandaskan nilai kebangsaan. Kaelan (2007) menegaskan bahwa pendidikan adalah wahana utama untuk menanamkan karakter publik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Integrasi nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap moral, etika, dan perilaku sehari-hari, sebagaimana ditegaskan oleh Notonogoro (1976) bahwa Pancasila adalah kristalisasi kepribadian bangsa yang harus menjadi pedoman hidup. Selain itu, pelatihan dan pembinaan budaya kerja aparatur negara berbasis Pancasila menjadi kunci agar birokrasi dan sistem pemerintahan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Magnis-Suseno (2003) menekankan bahwa dimensi moral identitas berperan penting dalam menguatkan kesadaran kolektif dan legitimasi institusi negara. Aparatur negara yang berkarakter dan beretika akan menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga nilai-nilai kebangsaan dapat terserap secara lebih luas. Kemudian menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan sejarah kebangsaan dan kegiatan kemasyarakatan juga menjadi upaya penting, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dan praktik gotong royong menjadi simbol nyata identitas bangsa di era globalisasi. Tilaar (2007) menekankan bahwa keterlibatan aktif warga dalam pembangunan sosial dan budaya memperkuat kohesi masyarakat. Gotong royong tidak hanya menumbuhkan solidaritas, tetapi juga menjadi medium praktik nilai Pancasila, menjadikan identitas nasional hidup, dinamis, dan relevan dalam konteks global saat ini.
Penulis : Fransiskus Sehadun
Identitas Nasional Indonesia: Pilar Persatuan di Tengah Keberagaman











