Kemerdekaan yang Tertunda: Polemik Bangsa di Usia 80 Tahun
Fransiskus Sehadun

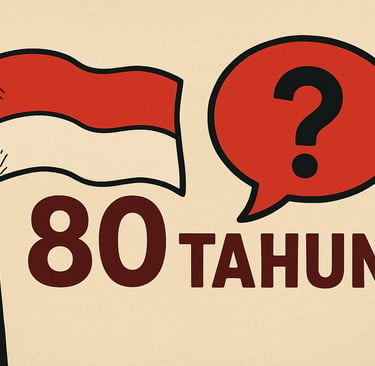
Indonesia kini telah memasuki usia delapan puluh tahun kemerdekaannya. Jika usia bangsa ini kita ibaratkan sebagai usia manusia, maka delapan dekade adalah masa ketika kedewasaan sudah sepenuhnya tercapai, masa ketika seseorang seharusnya mampu memetik hikmah dari pengalaman hidupnya dan akan lebih bijak, lebih arif, dan lebih bertanggung jawab. Namun, ketika kita menengok wajah bangsa hari ini, pertanyaan besar muncul: apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Apakah kemerdekaan yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus itu telah membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ataukah ia masih sebatas simbolik, sekadar bebas dari penjajahan kolonial tetapi belum terbebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan dan lain sebagainya.
Kemerdekaan pada mulanya dimaknai sebagai kebebasan dari dominasi asing. Para pendiri bangsa dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia merdeka agar dapat berdiri di atas kaki sendiri. Namun, sejak awal pula mereka menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Proklamasi hanyalah pintu gerbang menuju cita-cita yang lebih luhur: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Janji konstitusi ini telah berusia delapan puluh tahun, tetapi realitasnya masih jauh dari yang dicita-citakan.
Memang ada hal yang positif bangsa ini dan itu patut kita syukuri seperti Infrastruktur, demokrasi prosedural berjalan dengan pemilu rutin, angka kemiskinan menurun menurut data BPS, dan Indonesia semakin diperhitungkan dalam percaturan global. Namun, di balik itu semua, terdapat kesenjangan yang kian melebar antara segelintir orang yang menikmati hasil pembangunan dengan jutaan rakyat kecil yang masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Kemerdekaan akhirnya terasa timpang, karena yang satu berlari dalam kemewahan, sementara yang lain merangkak dalam keterbatasan.
Salah satu penyebab utama dari problem ini adalah kebijakan pemerintah yang sering kali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam teori negara kesejahteraan, negara seharusnya hadir sebagai pelindung utama rakyat, bukan sekadar wasit apalagi sebagai fasilitator kepentingan segelintir elit. Thomas Humphrey Marshall pernah menegaskan bahwa hak warga negara mencakup tiga dimensi: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sosial inilah yang menjamin setiap orang berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, serta jaminan kesehatan. Namun di Indonesia, hak-hak sosial itu kerap terabaikan seperti adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan pemberian tunjangan fantastis kepada pejabat justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih sibuk mengamankan kenyamanan elit daripada memperhatikan denyut nadi rakyat jelata.
Kekecewaan semakin memuncak ketika lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat, justru sibuk merawat kenyamanan dirinya sendiri. Dalam teori demokrasi modern, lembaga legislatif memiliki fungsi checks and balances untuk mengawasi pemerintah. Mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil kekuasaan. Akan tetapi, dalam praktiknya DPR sering kali bersekongkol dengan pemerintah. Kasus kenaikan tunjangan DPR hingga ratusan juta rupiah di tengah sulitnya kehidupan rakyat adalah bukti betapa jauhnya jarak antara elit politik dengan masyarakat yang diwakilinya. Demokrasi kita akhirnya kehilangan makna substantifnya, karena kekuasaan lebih berfungsi sebagai arena transaksi elit ketimbang sebagai alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Fenomena ini sejalan dengan analisis Jeffrey Winters tentang oligarki. Menurutnya, Indonesia pasca-Orde Baru tidak berubah menjadi demokrasi substantif, melainkan menjadi negara oligarki, di mana segelintir elit kaya memanfaatkan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan dan memperbesar keuntungan mereka. Hal ini juga ditegaskan Robison dan Hadiz dalam analisis mereka mengenai “oligarki pasca-Soeharto,” bahwa reformasi justru membuka ruang lebih besar bagi elit ekonomi-politik untuk menguasai panggung kekuasaan. Maka tak heran jika demokrasi di Indonesia kerap disebut hanya prosedural, karena esensinya dikuasai oleh kepentingan segelintir orang yang berputar di lingkar kekuasaan.
Akibat dari kebijakan yang tidak berpihak itu, keresahan masyarakat pun meningkat. Rakyat yang merasa diabaikan sering kali memilih jalan demonstrasi. Unjuk rasa yang awalnya damai tidak jarang berujung pada kericuhan, bahkan pembakaran fasilitas umum. Fenomena ini sesungguhnya adalah alarm keras bagi para penguasa bahwa ada jarak yang semakin lebar antara rakyat dan pemerintah. Dalam teori demokrasi partisipatoris, rakyat seharusnya dilibatkan bukan hanya saat pemilu lima tahunan, tetapi juga dalam proses penyusunan kebijakan. Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara, melainkan harus terus hidup dalam ruang dialog sehari-hari. Sayangnya, partisipasi rakyat di Indonesia masih dipandang sebagai ancaman ketertiban, bukan sebagai sumber legitimasi kebijakan.
Namun demikian, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa bangsa ini juga memiliki potensi besar untuk keluar dari lingkaran masalah tersebut. Jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan politik ke rel rakyat. Politik sejati bukanlah arena perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama. DPR harus direformasi secara mendasar, baik dalam mekanisme akuntabilitas maupun dalam budaya politik internalnya, agar mereka sungguh-sungguh menjadi representasi rakyat. Pemerintah harus belajar untuk membuka telinga dan hati, tidak hanya kepada investor dan elit, tetapi terutama kepada petani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan kelompok marjinal yang selama ini menjadi penopang bangsa.
Selain itu, partisipasi publik harus diperluas dan diperkuat. Teknologi digital seharusnya bisa menjadi jembatan yang mempertemukan aspirasi rakyat dengan pengambil kebijakan. Tetapi kanal partisipasi itu hanya bermakna jika pemerintah benar-benar mau mendengar. Lebih dari itu, pendidikan politik bagi rakyat perlu digalakkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam politik uang atau sekadar menjadi penonton di panggung demokrasi. Demokrasi hanya akan sehat jika rakyatnya sadar, kritis, dan berani memperjuangkan hak-haknya.
Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momen refleksi nasional. Kita sudah lepas dari penjajahan fisik, tetapi masih terjebak dalam penjajahan gaya baru: ketidakadilan, kesenjangan, dan dominasi oligarki. Polemik bangsa Indonesia hari ini bukan sekadar tentang kebijakan yang keliru, melainkan tentang arah perjalanan kita ke depan. Apakah kita akan terus membiarkan demokrasi dikooptasi oleh segelintir elit, ataukah kita berani mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi?
Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat bisa hidup dengan layak, ketika setiap anak mendapatkan pendidikan yang bermutu, ketika setiap keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, ketika para buruh dan petani dapat bekerja tanpa dihantui ketidakpastian, dan ketika setiap warga negara merasa dilindungi oleh negaranya. Itulah janji kemerdekaan yang masih tertunda, yang harus terus diperjuangkan. Tugas ini memang berat, tetapi tanpa perjuangan itu, kemerdekaan kita hanya akan tinggal sebagai slogan kosong dalam upacara tahunan. Indonesia yang berusia delapan puluh tahun ini harus memilih: apakah akan menjadi bangsa yang matang dan berdaulat bagi rakyatnya, atau sekadar menjadi negara tua yang lelah dan semakin terjebak dalam lingkaran oligarki.
Kemerdekaan yang Tertunda: Polemik Bangsa di Usia 80 Tahun











