Pancasila sebagai Falsafah Hidup bangsa Indonesia
Fransiskus Sehadun
Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, ada sebuah dasar filosofis yang menjadi fondasi negara baru itu. Dasar tersebut tidak lahir dari ruang kosong,melainkan hasil perenungan mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang sudah hidup ratusan tahun dalam masyarakat Nusantara. Dasar itu adalah Pancasila. Namun, Pancasila tidak berhenti pada statusnya sebagai dasar negara semata. Ia juga dimaknai sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu kristalisasi nilai-nilai luhur yang memberi arah bagi perjalanan bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika zaman. Pandangan inilah yang ditegaskan oleh Notonagoro (1975), bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan juga falsafah hidup bangsa Indonesia
Falsafah bisa di artikan juga filsafat dalam pengertiannya adalah cinta kebijaksanaan. Dalam perkembangan pemikiran modern, Kattsoff (1986) membedakan antara filsafat sebagai proses dan filsafah sebagai produk. Sebagai proses, filsafat adalah aktivitas berpikir kritis, sistematis, dan reflektif untuk mencari kebenaran. Sedangkan sebagai produk, filsafat adalah hasil dari aktivitas berpikir tersebut, berupa konsep, teori, atau sistem nilai yang dapat dijadikan pegangan hidup. Jika dilihat dari perspektif ini, maka Pancasila dapat dipahami sebagai falsafah hidup dalam arti produk: ia merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai, perenungan, dan konsensus bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah pedoman hidup bersama.
Melihat Pancasila sebagai filsafat yang berakar dalam kebudayaan Indonesia sebagaimana yang disampaikan Soerjanto (1994) bahwa Pancasila tidak boleh dipahami hanya sebagai konstruksi politik, melainkan sebagai refleksi dari nilai-nilai yang sudah mengakar dalam masyarakat. misalnya, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan religiusitas masyarakat Nusantara yang plural. Sila kedua tentang kemanusiaan menggambarkan pengakuan terhadap martabat manusia yang sejak dulu dijunjung tinggi dalam budaya gotong royong. Demikian pula sila ketiga tentang persatuan, yang lahir dari kesadaran bahwa bangsa yang beragam ini hanya bisa bertahan jika Bersatu, kemudian sila keempat mencerminkan bahwa segala sesuatu dalam mengambil keputusan harus melalui musyawarah dan mufakat, kemudian menjunjung tinggi nilai keadilan dalam hal apapun. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi formal, tetapi juga cermin dari jati diri bangsa.
Jika menelusuri lebih jauh, makna falsafah hidup dari Pancasila juga terlihat dalam cara bangsa ini mengelola keberagaman. Kaelan (2002) menjelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang bersifat integratif. Ia mampu merangkul perbedaan etnis, agama, bahasa, dan budaya dalam satu kerangka kebangsaan. Dalam perspektif ini, Pancasila bukan hanya pedoman normatif, tetapi juga perekat sosial yang memungkinkan Indonesia tetap utuh meski dihuni lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah. Tanpa falsafah hidup seperti Pancasila, sangat mungkin Indonesia akan terpecah-belah oleh kepentingan sempit kelompok atau daerah.
Selain itu bahwa fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup terlihat pula dalam perannya sebagai orientasi moral dan etis. Notonagoro (1975) menekankan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi pada saat yang sama juga sebagai sumber moral. Artinya, hukum di Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam sila keadilan sosial, terkandung kewajiban negara untuk menegakkan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memastikan setiap warga negara memperoleh hak dasar. Di sinilah Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan penyelenggaraan negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan.
Lebih jauh lagi, Pancasila sebagai falsafah hidup memiliki karakteristik yang khas. Pertama, ia bersifat terbuka, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi nilai dasarnya. Inilah yang dimaksud oleh Yudi Latif (2011), bahwa Pancasila bukan doktrin yang kaku, melainkan yang hidup bersama masyarakat. Kedua, Pancasila bersifat universal dimana nilai-nilainya bersifat universal seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan namun pada saat yang sama berakar pada pengalaman historis dan budaya bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila bersifat integratif karena mampu menjembatani perbedaan dan menghindarkan bangsa dari fragmentasi. Ketiga karakteristik ini menjadikan Pancasila tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga di masa depan.
Namun, dalam praktiknya, tantangan besar muncul ketika falsafah hidup itu tidak lagi dijadikan rujukan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus korupsi, intoleransi, dan konflik sosial yang menunjukkan adanya jurang antara nilai Pancasila dan kenyataan. Jika Pancasila benar-benar dijadikan falsafah hidup, maka setiap tindakan publik maupun privat seharusnya didasarkan pada semangat kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Sayangnya, dalam banyak hal, Pancasila sering hanya berhenti sebagai jargon politik. Inilah yang dikritisi oleh Soedjatmoko, bahwa bangsa ini sering gagal menginternalisasi nilai Pancasila dalam praktik sosial, sehingga yang muncul hanyalah retorika tanpa implementasi.
Meski begitu, relevansi Pancasila sebagai falsafah hidup tidak bisa diragukan. Dalam konteks globalisasi, misalnya, Pancasila dapat menjadi filter bagi masuknya nilai-nilai asing. Globalisasi membawa peluang, tetapi juga ancaman berupa konsumerisme, individualisme, dan hedonisme. Tanpa fondasi nilai yang kuat, bangsa ini bisa hanyut dalam arus tersebut. Di sinilah Pancasila berperan sebagai benteng moral sekaligus pedoman etis. Nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pegangan agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya di tengah gempuran budaya global.
Dari sisi pendidikan, Pancasila sebagai falsafah hidup juga menjadi orientasi penting. Ishaq (2021) dalam bukunya Pendidikan Pancasila menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berlandaskan Pancasila, karena hanya dengan cara itu generasi muda bisa memahami jati diri kebangsaan. Pendidikan Pancasila tidak boleh dipahami sebatas hafalan, melainkan harus menyentuh pembentukan karakter. Dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, pendidikan diharapkan melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila akan mampu mengimbangi derasnya arus modernisasi dengan akar budaya bangsa.
Dalam perjalanan sejarah, Pancasila juga membuktikan dirinya sebagai falsafah hidup yang adaptif. Pada era Orde Lama, Pancasila dihadapkan pada pergulatan ideologi besar seperti liberalisme dan komunisme. Pada era Orde Baru, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi politik yang menimbulkan trauma kolektif. Namun, pada era Reformasi, Pancasila kembali diposisikan sebagai falsafah hidup yang inklusif dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami distorsi, nilai dasar Pancasila tetap bertahan dan selalu menemukan relevansinya. Seperti yang dikatakan oleh Franz Magnis-Suseno (1995), Pancasila adalah titik temu yang menyatukan berbagai aliran pemikiran di Indonesia. Tanpa Pancasila, bangsa ini akan kehilangan arah karena tidak ada konsensus nilai yang bisa dijadikan pegangan bersama.
Sebagai falsafah hidup, Pancasila bukan hanya sesuatu yang abstrak, tetapi juga praksis. Ia hadir dalam keseharian: dalam gotong royong warga desa membangun jalan, dalam toleransi antarumat beragama yang saling menghormati hari raya masing-masing, dalam musyawarah warga untuk menyelesaikan persoalan bersama. Praktik-praktik sederhana ini menunjukkan bahwa Pancasila benar-benar hidup ketika nilai-nilainya dipraktikkan, bukan sekadar dihafalkan. Inilah yang membedakan falsafah hidup dengan sekadar ideologi formal: falsafah hidup mengakar dalam laku, bukan hanya dalam wacana.
Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dapat dipahami sebagai pedoman nilai yang lahir dari pengalaman historis, kebudayaan, dan konsensus kolektif bangsa. Ia berfungsi sebagai dasar negara, orientasi moral, sumber hukum, sekaligus pedoman etis bagi kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya yang terbuka, universal-partikular, dan integratif menjadikannya relevan sepanjang masa. Meski tantangan implementasi selalu ada, Pancasila tetap menjadi bintang penunjuk jalan, seperti yang dikatakan Abdulgani (1979), bahwa Pancasila adalah leitstar dan leitmotive bangsa Indonesia. Tanpa falsafah hidup seperti Pancasila, bangsa ini akan mudah goyah di tengah terpaan krisis dan dinamika global.
keberlangsungan Pancasila sebagai falsafah hidup sangat bergantung pada sejauh mana bangsa ini mau menginternalisasi dan mempraktikkannya. Ia tidak boleh berhenti sebagai simbol atau jargon, melainkan harus hadir dalam kebijakan, pendidikan, dan perilaku sosial. Tugas generasi sekarang adalah memastikan bahwa Pancasila tetap hidup, bukan sekadar tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Karena hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, bangsa Indonesia bisa menjaga keutuhan, martabat, dan masa depannya. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Jika Pancasila mati, maka matilah jiwa bangsa ini
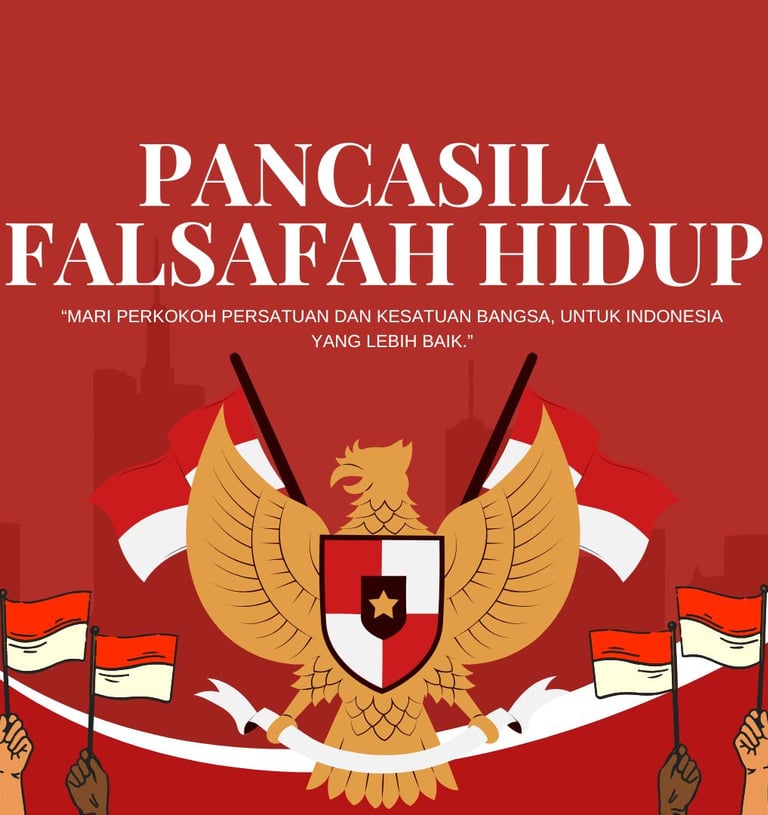
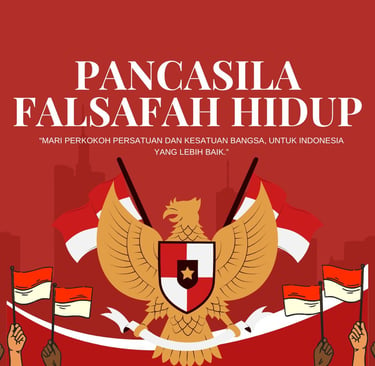
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP











